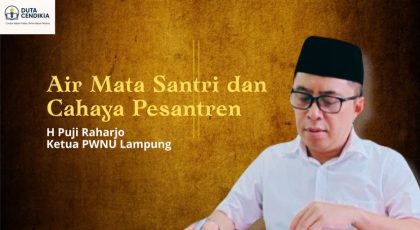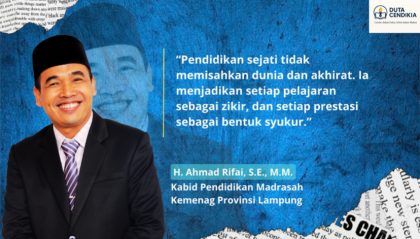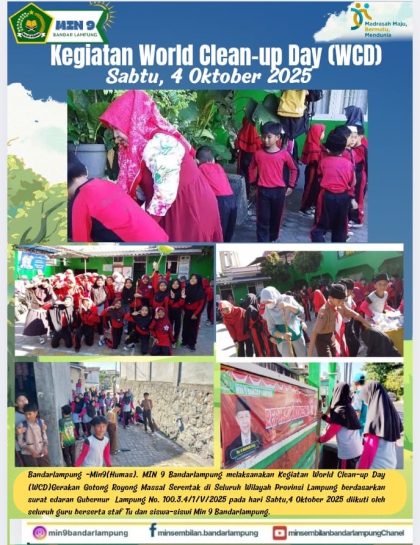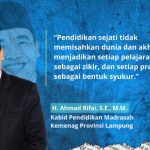Oleh : Ridho M Septiano – Aktivis Pendidikan
dutacendikia.id, Lampung – Sudah terlalu lama kita menyanjung guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ucapan itu terdengar luhur, tetapi di baliknya tersembunyi ironi yang tak mudah diabaikan. Di satu sisi, guru adalah arsitek peradaban yang memahat masa depan bangsa. Namun di sisi lain, mereka sering diperlakukan sekadar pelengkap kebijakan. Kita memuliakan mereka di panggung upacara, lalu melupakan suaranya di ruang perumusan keputusan.
Sebagai jurnalis yang setiap hari bergelut dengan isu pendidikan, sekaligus mahasiswa di fakultas pendidikan, saya menyaksikan paradoks itu makin nyata. Kita fasih berbicara tentang penghormatan kepada guru, tetapi abai ketika tiba saatnya bertindak. Padahal, jika bangsa ini sungguh ingin menapaki visi Generasi Emas 2045, pendidikan tak boleh berhenti sebagai jargon pembangunan. Ia harus menjadi fondasi strategis yang dijalankan dengan keberlanjutan, keadilan, dan keberanian moral.
Fenomena di lapangan memperlihatkan gejala yang mengkhawatirkan. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri menurun. Di berbagai daerah, termasuk di Lampung, orang tua mengeluhkan fasilitas yang terbatas, pelayanan yang menurun, dan semangat guru yang kian memudar. Sekolah swasta perlahan menjadi pilihan utama bagi mereka yang mampu, sementara sekolah negeri tertinggal sebagai pilihan bagi yang tak punya banyak pilihan. Ini bukan sekadar pergeseran selera, melainkan tanda krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Padahal sekolah negeri adalah wujud nyata tanggung jawab negara terhadap keadilan sosial. Bila kepercayaan itu hilang, jurang sosial akan semakin lebar. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan kesetaraan justru berubah menjadi tembok pemisah. Paulo Freire mengingatkan, pendidikan yang tidak membebaskan hanya akan melanggengkan ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, sekolah negeri yang gagal menjaga kualitasnya berpotensi melahirkan kembali ketimpangan yang seharusnya diberantas.
Akar masalah pendidikan kita sesungguhnya bukan semata pada sistem, tetapi pada manusia yang menggerakkannya: guru. Di balik dedikasi dan ketulusan mereka, ada luka yang tak pernah sembuh. Luka tentang penghargaan dan kesejahteraan. Data Kemendikbudristek 2023 mencatat lebih dari 700 ribu guru honorer di Indonesia, banyak di antaranya menerima gaji di bawah upah minimum, bahkan hanya tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah per bulan. Di Lampung, kisah serupa masih berulang. Puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah guru kita perlakukan sebagai profesi atau hanya simbol pengabdian? Jika guru adalah profesi, maka penghargaan dan kesejahteraan adalah hak yang melekat. Namun jika profesi ini terus dipandang sebagai panggilan jiwa semata, maka sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa” tak lebih dari romantisme kosong. John Dewey, filsuf pendidikan asal Amerika, pernah mengatakan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada kualitas pendidiknya. Mengabaikan guru berarti mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.
Konstitusi sebenarnya telah memberi dasar kuat. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan alokasi minimal dua puluh persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Angka itu bahkan lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD. Namun laporan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan, sebagian besar dana pendidikan terserap pada belanja rutin: gaji pegawai, tunjangan struktural, dan biaya birokrasi. Porsi untuk peningkatan mutu pembelajaran masih jauh dari ideal.
Inilah paradoks yang paling mencolok. Kita memiliki komitmen finansial, tetapi kehilangan arah moral. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menulis bahwa pembangunan sejati bukan soal pertumbuhan angka, melainkan soal memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermakna. Pendidikan seharusnya menjadi jalan pembebasan itu, bukan sekadar alat administratif yang memburu target.
Banyak negara telah membuktikan bahwa keberhasilan pendidikan tak bergantung pada besar anggaran semata. Finlandia hanya mengalokasikan sekitar tujuh persen PDB-nya untuk pendidikan, namun memberi otonomi luas kepada guru dan menempatkan mereka sebagai pusat inovasi. Estonia, dengan sumber daya terbatas, mampu menembus papan atas tes PISA berkat fokus pada digitalisasi dan kurikulum yang fleksibel. Bahkan Thailand, dengan anggaran lebih kecil dari Indonesia, menjaga pemerataan akses melalui efisiensi dan pelatihan guru yang berkelanjutan.
Semua contoh itu menunjukkan hal yang sama: keberanian politik dan moral jauh lebih menentukan daripada sekadar angka di atas kertas. Tanpa keberanian menempatkan guru dan murid sebagai pusat kebijakan, alokasi dua puluh persen APBN hanya akan menjadi formalitas tanpa makna.
Refleksi bagi Indonesia jelas. Sekolah negeri harus direformasi agar kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Kesejahteraan guru honorer perlu dituntaskan dengan langkah yang adil dan manusiawi. Anggaran pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan menumpuk di birokrasi. Kurikulum pun harus berpihak pada pembebasan dan kreativitas, bukan pada kepatuhan administratif.
Namun perubahan tidak akan berarti jika cara pandang kita terhadap pendidikan tetap sama. Generasi Emas 2045 hanya akan menjadi slogan jika sekolah negeri tetap dianggap pilihan terakhir dan guru masih diperlakukan sebagai tenaga sukarela. Generasi emas hanya akan lahir dari sistem yang menempatkan pendidikan sebagai investasi peradaban, bukan beban keuangan negara. Program seperti Merdeka Belajar, pengangkatan ASN-PPPK, atau digitalisasi sekolah memang langkah awal yang penting, tetapi tak cukup tanpa konsistensi politik dan keberanian moral.
Tulisan ini tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keyakinan bahwa pendidikan adalah jantung peradaban. Bangsa besar tidak dibangun oleh gedung megah atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh guru yang dihormati, sekolah yang bermartabat, dan generasi yang tercerahkan. Kita sudah memiliki komitmen anggaran. Yang kita butuhkan kini hanyalah kemauan menata ulang prioritas dan menempatkan pendidikan di pusat kehidupan bangsa.
Jika hal itu terjadi, Generasi Emas 2045 tidak lagi sekadar visi di atas kertas. Ia akan tumbuh di setiap ruang kelas, di setiap tangan guru, dan di setiap jiwa anak bangsa yang percaya bahwa belajar adalah bentuk paling luhur dari mencintai negeri ini.